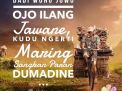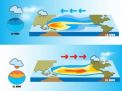Pada abad ke-2 sampai dengan abad ke-14 sebagian besar penduduk Jawa memeluk agama Hindu. Para pemuka agama Hindu selain menyebarkan agama juga memberi piwulang (ajaran) tentang cara bercocok tanam, membatik, membaca dan menulis sehingga akhirnya bahasa Hindu (Sansekerta) bercampur dengan bahasa setempat yang melahirkan bahasa baru yang disebut bahasa Jawa kuno (Purwadi, dkk, 2005:4). Bahasa ini terus berkembang dan mengalami perubahan sehingga menghasilkan kata kata Kawi dan selanjutnya menjadi bahasa Jawa yangada sekarang ini.
Sampai akhirnya suatu dinasti baru muncul yaitu dinasti Mataram dan mengubah tatanan sosial. Dinasti ini ingin menunjukkan bahwa mereka berasal dari dinasti yang terpilih. Sehingga mereka menciptakan suatu mekasnisme untuk menciptakan jarak sosial. Dan alat untuk menciptakan jarak sosial iniadalah dengan mengembangkan tatanan bahasa Jawa Ngoko – Kromo (Purwadi, dkk, 2005:13). Setelah Mataram mengubah statusnya dari kabupaten menjadi kerajaan, berbagai upaya dilakukan untuk mengukuhkan kedudukannya yang baru sebagai pemegang supremasi tertinggi di Jawa. Upaya tersebut diantaranya ada yang bercorak politis dan militer, mistis dan magis religious serta kultural.
Diantara upaya konsolidasi yang bercorak kultural terdapat pengembangan sastra Babad dan pengembangan bahasa Jawa dengan tatanan Ngoko – Kromo (tingkat rendah atau kasar – tingkat tinggi atau halus). Sastra Babad dikembangkan oleh dinasti Mataram sebagai pembangunan politik (G. Moedjanto 1987 : 41). Terdapat beberapa fungsi penggunaan Ngoko – Kromo dalam masyarakat Jawa. Pertama, sebagai norma pergaulan. Kedua, sebagai tata unggah ungguh. Ketiga, sebagai alat untuk menyatakan rasa hormat dan keakraban. Keempat, berfungsi sebagai pengatur jarak sosial (social distance). Dalam kaitannya dengan pengembangan kekuasaan.

Pada masa pemerintahannya Sultan Agung mengembangkan sejumlah unsur baru dalam kebudayaan, meskipun beberapa diantaranya sudah kelihatan akarnya pada masa masa sebelumnya.diantara unsur unsur baru yang dikembangkan adalah pembuatan tarikh baru, yaitu tarikh Jawa, pembaharuan perayaan Grebeg, penabuhan gamelan Sekaten, penciptaan tradisi keraton yang baru dan dalam pengenmbangan sastra Jawa khususnya Babad. Sultan Agung mempunyai minat yang khusus dalam mengembangkan sastra Babad ini (G. Moedjanto, 1987: 57)
Dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah patrap. Selain patrap, masyarakat Jawa juga mengenal tutur kata atau yang sering dikenal dengan istilah unggah ungguh.
Karena itu semua, lahirlah pepatah “Ajining raga tumata ing busana, ajining dhiri gumantung kedaling lathi.” Pepatah tersebut menyuratkan makna, baik serta buruknya seseorang bisa dinilai dari cara berpakaian serta bebicara.
Akan tetapi, perubahan zaman tidak bisa dihindari. Perlahan namun pasti, nilai-nilai unggah ungguh di Jawa mengalami pergeseran yang bisa dilihat dari tutur bahasa generasi Jawa saat ini.
Kini banyak generasi Jawa yang enggan, bahkan merasa malu, manakala harus berkata dengan menggunakan bahasa krama. Mereka menilai unggah ungguh yang ada di Jawa terkesan rumit. Makanya, banyak generasi sekarang malas untuk belajar dan akhirnya lupa.
Akan tetapi, sangat tidak adil manakala saya hanya mengambil dari satu sisi saja. Bagaimana jika ternyata selama ini orangtuanya tidak pernah mengajarkan unggah ungguh bahasa Jawa?
Sebenarnya saya tidak ingin juga mengambil peran sebagai hakim tutur kata. Namun terkadang, sebuah kejadian memaksa diri kita untuk memberikan analisis lebih dalam.
(Disadur dari berbagai sumber)













.jpg)